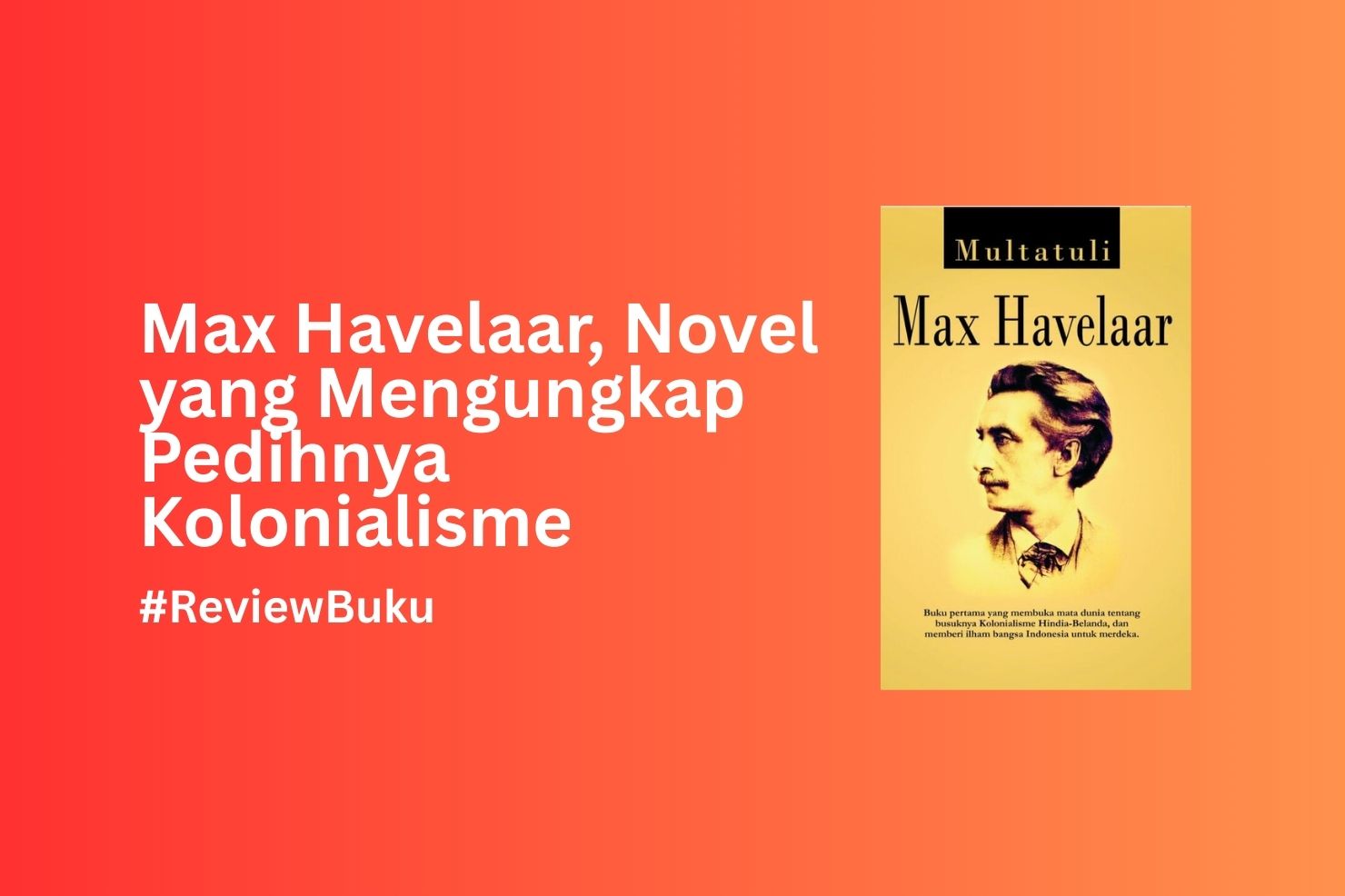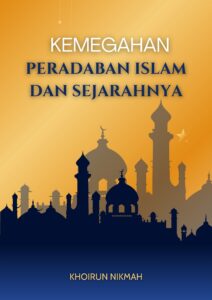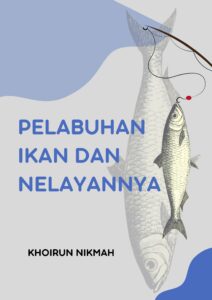Penulis :Reggie Baay
Penerbit :Komunitas Bambu
Tahun Terbit :2017
Buku ini membuat saya bergidik saat membaca judulnya. Lebih miris lagi membaca isi dari buku yang dalam judul aslinya yakni De Nyai: Het oncubinaat in Nederlands-Indie. Karya ini merupakan karya anak Indonesia yang dibesarkan di negeri Belanda. Sejak zaman kolonial nasip wanita sangatlah rendah, apalagi dengan predikat seorang nyai atau gundik yang bisa dikatakan dengan wanita simpanan orang Belanda, selain itu si Nyai juga dijadikan pembantu rumah tangga para orang orang Eropa di Hindia Belanda. Bagi para gundik tidak ada pilihan lain selain memasrahkan diri mereka menjadi wanita orang Eropa karena keterbatasan ekonomi dan desakan pemenuhan kebutuhan yang pada masa kolonial sering terjadi kelaparan.
Kata Nyai yang dipakai dalam buku ini berasal dari bahasa Bali. Kemunculan kata tersebut berbarengan dengan kemunculan perempuan Bali yang pada abad ke 17 menjadi budak atau gundik orang orang Eropa di wilayah pendudukan VO C. Sepanjang abad ke 19, banyak orang orang Eropa yang terus menggunakan julukan-julukan yang kurang cerdas dan menghina secara terang terangan. Julukan yang paling halus adalah inlandse huishoudster (pembantu rumah tangga pribumi). Penambahan kata pribumi sebenarnya sudah anah dan tidak perlu. Pada waktu itu jelas tidak ada pembantu rumahtangga Eropa dalam koloni. Nyai juga berarti seorang perempuan yang mengurus rumah tangga. Nyai di HIndia Belanda dipandang rendah.
Di dalam tangsi tangsi tentara kolonial, para nyai biasanya disebut dengan moentji. Moentji merupakan pelesetan dari kata mondje (mulut kecil). Para gundik juga disebut dengan meubel (perabot) atau inventarisstuk (barang inventaris) sebutan itu dapat diartikan secara harfiah karena pada waktu pelelangan yang dilakukan oleh orang Eropa yang akan pindah atau kembali ke negerinya, para nyai pun ikut dilelang sebagai dari inventaris mereka. Para nyai kerap disamakan dengan boek (buku) atau wondenbook (kamus). Karena para nyai membantu menerjemahkan bahasa pribumi kepada suami atau majikan mereka. Orang Belanda mengganggap Nyai rendah dan tidak bisa disejajarkan dengan bangsa Eropa yang berkulit putih.
Orang orang Eropa di HIndia Belanda menganggap gundik adalah fase dalam menyiapkan kehidupan berumah tangga sebelum mereka meminang wanita Eropa. Jika para majikan gundik sudah mau menikah, maka gundik dirumah harus bersiap siap angkat kaki dari rumah majikan/suami mereka. Terkadang mereka malu jika bersama Nyai dan anak anak yang berasala dari pergundikan. Para suami ini kadang tidak member nafkah setelah mereka menikah secara sah dengan wanita Eropa. Dengan sadis mereka menggambarkan nyai sebagai orang yang bodoh, perkembangan kejiwaan yang buruk, dan jelek secara fisik. Seolah olah para nyai berada pada tahapan sebelum evolusi manusia. Perumpaan yang mengerikan bagi seorang wanita pribumi yang bekerja sebagai nyai “pembantu rumah tangga”.
Kebiasaan di antara orang orang Eropa tidak memanggil nyai yang hidup bersama mereka dengan nama depannya, namu cukup menggunakan nama kelompok juga telah menjelaskan hubungan mereka. Para gundik sering dipanggil Mina, Sarina (dalam tangsi KNIL), Deli Kartina dalam perkebunan. Anak yang lahir dari pergundikan baru mengetahui nama ibu mereka ketika sudah dewasa dan membaca akta pengakuan mereka.
Pergundikan di tangsi militer amat bobrok lagi perilakunya. Anak anak yang masih 12 tahun sudah jadi gundik para anggota KNIL rendahan. Para gundik yang sudah berumur 30 tahun harus bersiap diri disuir dari tangsi dengan menerima surat lepas. Nasip nyai yang diusir dengan surat lepas mengalami kegoncangan jiwa yang mendalam, karena para nyai tidak mungkin kembali ke kampong mereka yang mayoritas muslim. Orang kampung pasti menolak kedatangannya karena telah melakukan perbuatan zina dengan seorang kafir. Serdadu KNIL yang tidak memiliki uang pun tidak mau menjadikan nyai yang sudah tua menjadi gundiknya.
Anak anak yang dilahirkan dari hasil pergundikan kerap disebut voorkinderen. Sebutan ini muncul karena mereka lahir dari hubungan laki laki Eropa sebelum akhirnya menikah dengan perempuan Eropa. Sejak tahun 1828 para laki laki eropa di dalam koloni diperbolehkan mengakui anak anak mereka yang lahir dari hubungan pergundikan. Pilihan lainnya adalah dengan tidak mengakui tapi mendaftarkan mereka di dalam daftar kelahiran. Pendaftaran ini mewajibkan sang ayah Eropa untuk merawat dan mendidik anak anak tersebut. Pilihan terakhir ini merupakan awal dari fenomena khas kolonial yang membalikkan nama keluarga. Anak anak didaftarkan dan diberikan nama keluarga sang ayah, namun urutan huruf dibalik. Pieterse menjadi Esreteip, an Riemsdijk menjadi Kijdsmeir dan Jansen menjadi Nesnaj.
Orang eropa yang kaya biasanya anak yang diperoleh dari hasil pergundikan dialihkan kepada orang Eropa lain. Pada tahun 1848 orang orang Kristen Eropa di Hindia Belanda diizinkan untuk menikah dengan orang non Kristen. Para orang eropa dapat melangsungkan pernikahan dengan nyai mereka pada 1848. Kesempatan itu tidak banyak dilakukan oleh orang eropa, karena menikahi Nyai berarti pengrusakan terhadap kode kolonial. Orang eropa yang melakukan perkawinan denga pribumi akan menempatkan dirinya diluar masyarakat dan tidak memperoleh karier yang tinggi.
Status anak anak dari hasil pergundikan di tangsi nasipnya ada 4 kemungkinan, pertama sang nyai dan anak anak ikut ke tempat baru bersama anggota militer, kedua anggota militer yang dipindahkan tetapi meninggalkan begitu saja nyai dan anak-anak, ketiga sang nyai dan anak-anak dialihkan kepada rekan yang masih tinggal di Hindia Belanda dan yang keempat sang anggota militer membawa anak anak ke suatu temapat sedangkan sang nyai ditinggalkan begitu saja. Meskipun ada kasus beberapa gundik dibawa serta ketempat yang baru. Anak anak hasi pergundikan mayoritas tidak diakui keberadaannya oleh ayah mereka, anak anak yang tidak diakui menyulut kebencian yang mendalam di jiwa mereka. Pada abad ke 20 pergundikan dicela dengan tajam dan mendapat banyak kritikan. Setelah mabaca karya ini sebagai perempuan patut bersyukur, kehidupan kelam ini tidak terjadi dan kemiskinan di negeri ini tidak separah masa kolonial.