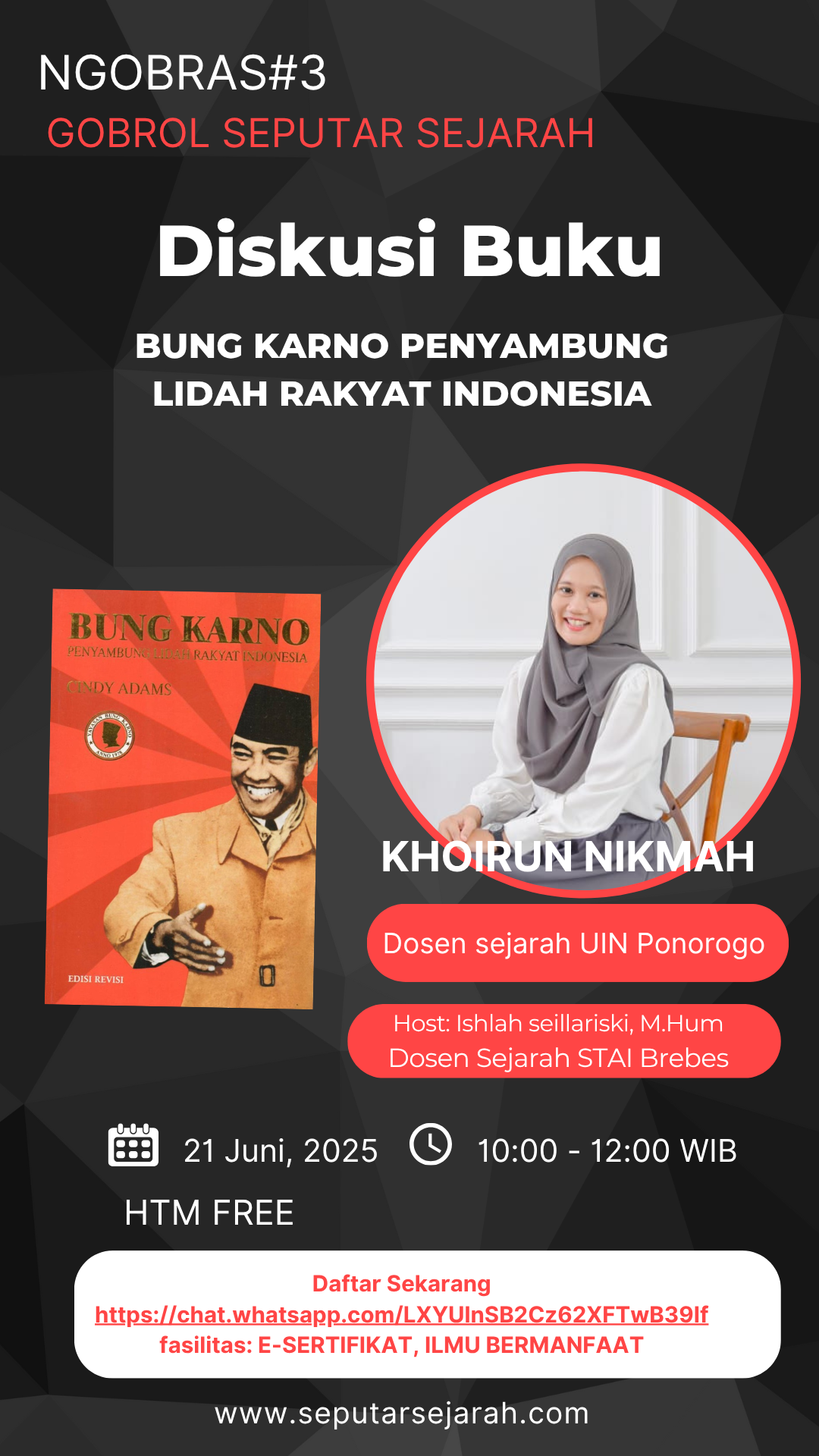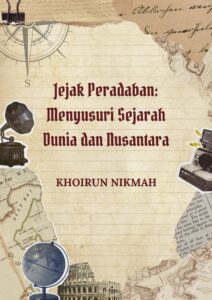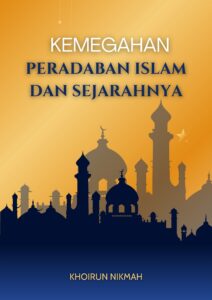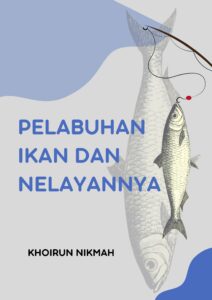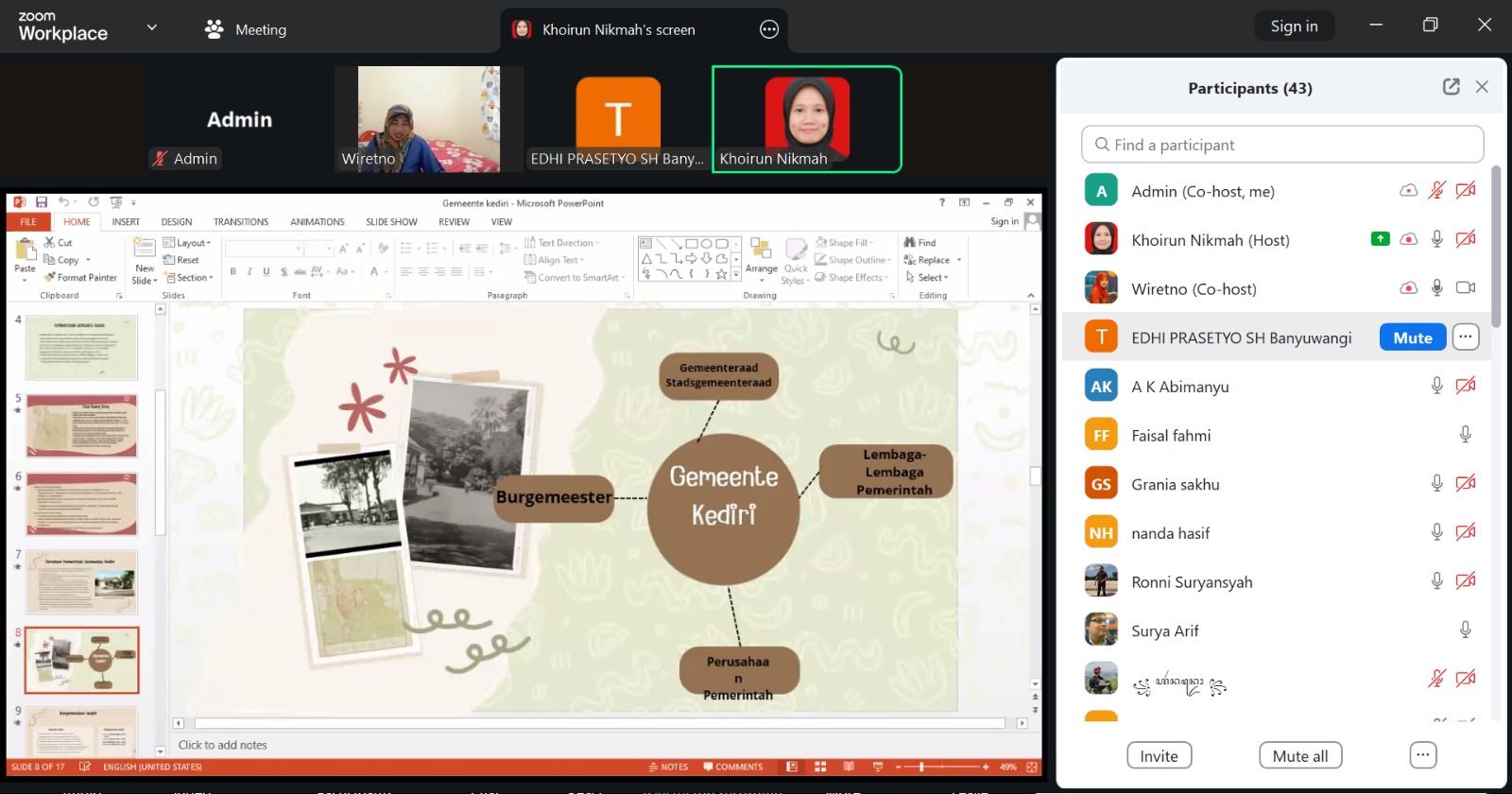
Seputarsejarah.com kembali lagi menyelenggarakan Ngobrol Seputar Sejarah Sesi 4 (#NGOBRAS4) pada hari Senin 20 Oktober 2025 melalui saluran ZOOM. Pemateri dalam diskusi kali ini adalah Wiretno, S.Hum penulis buku Gemeente Kediri (Dinamika Kota Kediri Masa Penjajahan Jepang). diskusi online ini dihadiri 40 peserta yang sangat antusias. berikut hasil dari bedah buku :
Kota Kediri merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang memiliki sejarah panjang dan menarik dalam perjalanan administrasi kolonial hingga masa pendudukan Jepang. Di bawah dua rezim yang berbeda, Kediri mengalami perubahan besar, baik dalam bidang pemerintahan, sosial, maupun ekonomi. Dua periode penting yang menandai sejarah kota ini adalah masa Gemeente Kediri (1906–1942) dan Kediri-Syuu (1942–1945). Keduanya menunjukkan bagaimana Kediri berkembang dari kota kolonial yang modern menjadi wilayah strategis dalam sistem pemerintahan militer Jepang.
Masa Gemeente Kediri berawal dari diberlakukannya Decentralisatie Wet tahun 1903 yang memungkinkan beberapa kota di Hindia Belanda memperoleh otonomi pemerintahan. Kediri termasuk salah satu kota yang memenuhi syarat dan pada tanggal 1 April 1906 ditetapkan sebagai Gemeente Kediri. Status ini kemudian meningkat menjadi Stadsgemeente pada 1 Januari 1928. Sejak saat itu, Kediri berubah menjadi kota yang terkelola dengan baik, lengkap dengan struktur pemerintahan, tata ruang, serta fasilitas publik yang modern. Kawasan barat Sungai Brantas menjadi pusat kegiatan pemerintahan dan pemukiman Eropa, sedangkan bagian timur berkembang sebagai wilayah perdagangan dan pemukiman masyarakat Tionghoa serta bumiputra.
Dalam bidang pendidikan, Kediri memiliki beberapa sekolah modern seperti Frobelschool, Europesche Lagere School (ELS), dan Holland Inlandsche School (HIS). Sekolah-sekolah ini menjadi simbol kemajuan pendidikan di kota tersebut. Selain itu, terdapat pula sekolah bagi anak-anak Tionghoa seperti Tiong Hwa Hwee Kwan (THHK) dan Chineesche Meisjesschool. Perkembangan pendidikan ini memperlihatkan bahwa Kediri telah menjadi salah satu pusat pendidikan penting di wilayah Karesidenan Kediri pada masa itu. Di bidang kesehatan, pemerintah kota juga membangun rumah sakit bumiputra dan sejumlah klinik swasta. Hal ini menjadi cerminan dari meningkatnya perhatian terhadap kesehatan dan kebersihan lingkungan kota.
Perkembangan ekonomi di masa Gemeente Kediri juga sangat pesat. Kota ini memiliki empat pasar utama, yaitu Pasar Alon-Alon, Pasar Bangsal, Pasar Pahing, dan Pasar Plaboean. Pasar-pasar tersebut dikelola secara profesional oleh perusahaan pasar kota yang disebut passerbedrijf. Pemerintah kota juga mengatur kebijakan transportasi, memperbaiki jalan, membangun halte bus, serta menyediakan fasilitas publik seperti rumah potong hewan dan penerangan jalan. Semua itu menunjukkan bahwa Kediri pada masa kolonial Belanda telah menjadi kota yang maju dan terencana dengan baik.
Namun, masa kejayaan tersebut berakhir ketika tentara Jepang datang pada tahun 1942. Kediri menjadi salah satu wilayah penting dalam strategi militer Jepang di Jawa Timur. Pada tanggal 5 Maret 1942 terjadi pertempuran di Jembatan Brantas yang menjadi awal dari pendudukan Jepang di kota ini. Sejak saat itu, sistem pemerintahan kota berubah total. Melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1942, Kediri ditetapkan menjadi Syuu, wilayah administratif setingkat karesidenan yang membawahi Kediri, Blitar, Tulungagung, dan Nganjuk. Dewan kota atau Gemeenteraad dihapus, digantikan oleh struktur militer di bawah pengawasan Jepang.
Meskipun masa pendudukan Jepang berlangsung singkat, dampaknya sangat besar bagi masyarakat Kediri. Pemerintah militer Jepang memanfaatkan potensi ekonomi wilayah Kediri, terutama di bidang pertanian dan perikanan. Tahun 1943, Kediri tercatat sebagai salah satu daerah penghasil ikan terbaik di Indonesia. Namun di balik keberhasilan tersebut, rakyat mengalami penderitaan berat. Jepang memaksa masyarakat bekerja dalam proyek besar seperti pembangunan Terowongan Neyama di Campurdarat. Pekerjaan ini melibatkan sekitar 1,8 juta romusha yang bekerja di bawah tekanan dan penyiksaan. Proyek yang diklaim sebagai terowongan pengendali banjir itu selesai dalam waktu satu setengah tahun dan diresmikan pada 31 Juli 1944.
Selain kerja paksa, masyarakat Kediri juga menghadapi kelaparan dan wabah penyakit. Meskipun daerah ini dikenal sebagai penghasil padi, banyak warga yang menderita kekurangan pangan karena hasil panen diambil untuk kebutuhan perang Jepang. Wabah patek (kusta) menyerang ribuan penduduk, sementara angka kematian ibu dan bayi meningkat tajam. Kondisi ini menggambarkan betapa beratnya kehidupan masyarakat Kediri di bawah pemerintahan militer Jepang.
Namun, dari masa penuh penderitaan itu juga muncul semangat perlawanan. Kediri menjadi salah satu pusat penting pergerakan militer bentukan Jepang, seperti Seinendan, Keibodan, Fujinkai, hingga PETA (Pembela Tanah Air). Dari organisasi inilah lahir tokoh Soeprijadi, pemimpin pemberontakan PETA yang menjadi simbol keberanian dan nasionalisme rakyat Indonesia melawan pendudukan Jepang. Semangat perjuangan inilah yang kemudian menjadi bagian penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia.
Dua periode sejarah tersebut — Gemeente Kediri dan Kediri-Syuu — menggambarkan dua wajah Kediri yang kontras. Pada masa Belanda, Kediri berkembang sebagai kota modern dengan sistem pemerintahan yang tertata dan kehidupan ekonomi yang stabil. Namun di masa Jepang, kota ini berubah menjadi wilayah penderitaan sekaligus kebangkitan semangat perjuangan rakyat. Kini, setiap sudut kota Kediri, mulai dari Jembatan Lama Brantas hingga kawasan Dhoho, menyimpan jejak sejarah dari dua masa yang sangat berbeda. Dari kota kolonial yang megah hingga kota perjuangan yang tangguh, Kediri tetap menunjukkan keteguhan jiwanya dalam menghadapi perubahan zaman.
.